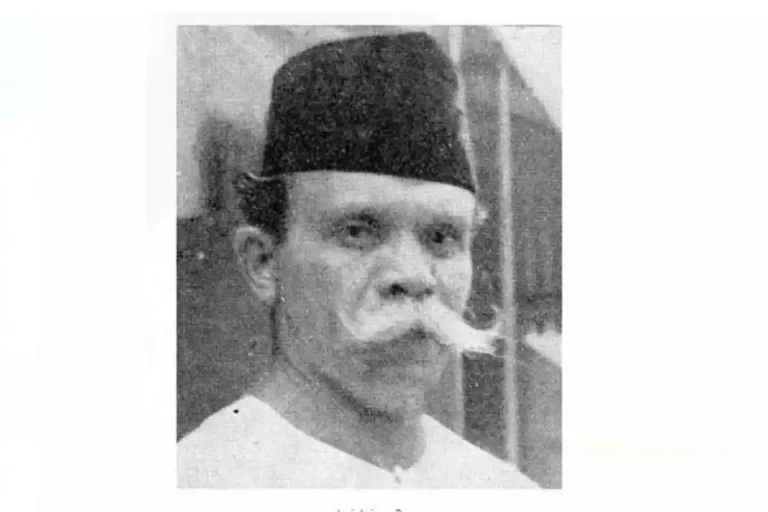Wacana redenominasi rupiah selalu muncul kembali ketika stabilitas ekonomi terlihat cukup terjaga. Di permukaan, menghapus tiga nol dari rupiah tampak seperti langkah sederhana sebagai sekadar penyesuaian angka. Akan tetapi, di balik itu, redenominasi adalah kebijakan psikologis, teknis, dan politis yang punya konsekuensi luas, baik positif maupun negatif.
Itulah sebabnya pemerintah sejak lama memilih berhati-hati karena ia bukan kebijakan mendesak, tetapi juga bukan ide yang bisa diabaikan. Di satu sisi, redenominasi menawarkan kesempatan memperbaiki persepsi terhadap mata uang nasional. Rupiah dengan angka yang “lebih pendek” membuat transaksi menjadi lebih efisien, pembukuan lebih ringkas, dan sistem pembayaran tidak lagi dibebani digit berlebihan.
Banyak negara yang sukses melakukan redenominasi—seperti Turki, Rumania, atau Korea Selatan—mengalami peningkatan citra mata uang secara internasional serta penyederhanaan administrasi ekonomi secara signifikan.
Indonesia sendiri sudah memiliki prasyarat penting: inflasi relatif terkendali dalam satu dekade terakhir, digitalisasi ekonomi makin luas, dan sistem pembayaran modern sudah matang. Semua ini membuat proses transisi lebih mudah dilakukan.
Efek psikologis juga penting. Harga makanan yang tadinya “Rp25.000” menjadi “Rp25” dapat menurunkan persepsi bahwa barang di Indonesia “mahal”, sekalipun nilai riil tidak berubah. Dalam konteks kepercayaan publik, persepsi stabilitas rupiah dapat naik karena masyarakat melihat pemerintah cukup percaya diri untuk melakukan redenominasi.
Dengan kata lain, redenominasi bisa menjadi sinyal positif bahwa ekonomi berada dalam fase dewasa dan stabil. Sinyal ini penting bagi investor, industri pariwisata, dan mitra perdagangan asing yang selama ini melihat rupiah sebagai mata uang dengan digit terlalu panjang.
Namun, sisi lain redenominasi tidak bisa dipungkiri. Semua manfaat tersebut tidak gratis. Tantangan utamanya adalah transisi. Penggantian label harga, penyesuaian sistem akuntansi, perubahan perangkat lunak perbankan, hingga edukasi publik memerlukan biaya besar.
Negara akan mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi dan percetakan uang baru, sementara pelaku usaha harus menyesuaikan seluruh sistem operasionalnya. Bagi UMKM yang masih manual, ini bisa menjadi beban tambahan.
Risiko psikologis juga tidak kecil. Meski redenominasi berbeda dari sanering (pemotongan nilai uang), sebagian masyarakat mungkin salah paham dan menganggapnya sebagai “pengurangan nilai tabungan”.
Ketidakpahaman ini dapat memicu penarikan uang besar-besaran atau ketidakpercayaan pada sistem keuangan, sebuah situasi yang justru ingin dihindari pemerintah. Negara lain pernah mengalami hal ini. Ketika sosialisasi buruk, masyarakat panik meski nilai uang sebenarnya tidak berubah.
Selain itu, Indonesia memiliki karakter ekonomi yang beragam. Di satu daerah, sistem pembayaran sudah serba digital; di daerah lain, ekonomi masih berjalan tunai dan informal. Redenominasi memerlukan kesiapan merata.
Jika tidak, kesalahan konversi harga, kebingungan transaksi, hingga potensi penyalahgunaan (seperti pedagang yang “membulatkan harga seenaknya”) bisa terjadi dan memicu inflasi psikologis. Dampak seperti ini tidak tampak dalam model ekonomi, tetapi nyata dalam perilaku pasar.
Karena itu, redenominasi tidak bisa diperlakukan sebagai proyek teknis semata. Ia adalah proses budaya dan komunikasi publik. Keberhasilannya lebih ditentukan oleh tingkat literasi, efektivitas sosialisasi, dan koordinasi antar lembaga daripada oleh rumus ekonomi. Indonesia dapat belajar dari Turki dan Rumania yang sukses karena proses transisinya bertahap, transparan, dan disertai stabilitas politik yang kuat.
Pada akhirnya, redenominasi adalah kebijakan dua sisi. Ia menawarkan penyederhanaan sistem ekonomi, peningkatan citra rupiah, dan efisiensi transaksi. Namun ia juga membawa risiko penyesuaian yang kompleks dan respons psikologis masyarakat yang tidak selalu bisa diprediksi.
Penulis: Ahmad Bagus Kazhimi