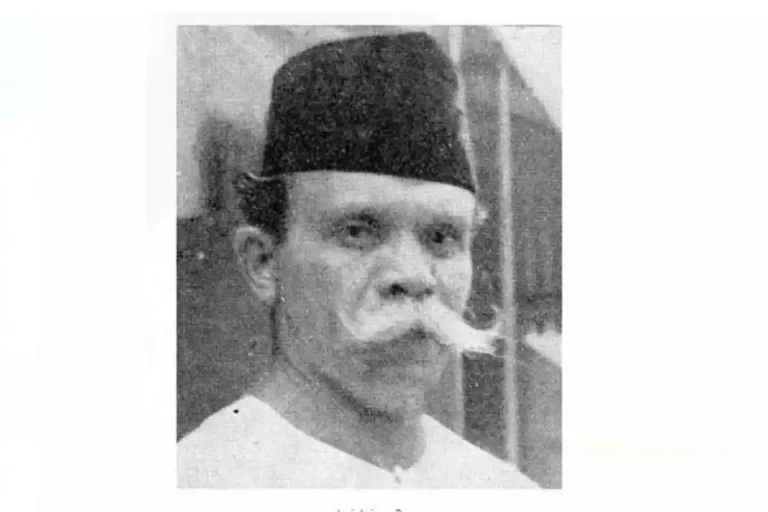Sejak awal 2025, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program yang cukup ambisius, yakni mendirikan sebanyak 200 Sekolah Rakyat berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Rencananya, pada tahun pertama disapkan 53 lokasi Sekolah Rakyat yang siap diresmikan pada Juli 2025 melalui renovasi gedung milik Kementerian Sosial, sementara 147 fasilitas tambahan menunggu persetujuan lahan dari pemerintah daerah.
Dari data yang dirangkum Badan Pusat Statistik (BPS) dipetakan bahwa lokasi-lokasi tersebut menjadi “kantong kemiskinan” dengan proporsi anak usia sekolah yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan formal cukup signifikan.
Kementerian PUPR dan pihak lokal daerah sudah menyediakan lahan seluas 5–8 hektare di mana lebih dari 200 pemerintah daerah mendukung, sementara pusat menyediakan dana APBN untuk infrastruktur dan operasional. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga berencana melibatkan pihak swasta dalam membiayai 100 sekolah berikutnya
Secara teknis, kurikulum yang digunakan akan berbasis standar nasional, namun mengadopsi sistem multi-entry dan multi-exit sehingga siswa bisa masuk dan lulus sesuai kesiapan dan latar belakang pendidikan sebelumnya.
Model asrama (boarding school) ini juga bertujuan menjamin kebutuhan gizi dan karakter siswa sehingga mereka juga diharapkan menjadi agen perubahan yang memutus mata rantai dari kalangan kemiskinan ekstrem.
Kebijakan ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata, sekaligus memberantas kemiskinan dari akarnya. Namun, jika kita telaah lebih dalam, gagasan ini justru menyimpan banyak persoalan mendasar yang patut dipertanyakan.
Apa dan mengapa sekolah rakyat ini penting? Sebenarnya, sekolah rakya ini untuk apa? Sudahkah ia melalui kajian yang utuh dan komprehensif agar konsep ini tak berujung pada hal yang sia-sia?
Secara konseptual, Sekolah Rakyat terlihat seperti ide yang inklusif. Akan tetapi, dalam implementasinya, kebijakan ini justru mengarah pada segregasi pendidikan. Bayangkan ketika anak-anak dari keluarga miskin dikumpulkan dalam satu jenis sekolah khusus, berasrama, terpisah dari sistem sekolah umum yang diakses oleh kalangan menengah dan atas.
Bukankah ini justru menciptakan tembok baru dalam pendidikan Indonesia, yakni antara “sekolah rakyat” dan “sekolah bukan rakyat”? Apakah pendidikan seharusnya dibangun untuk menyatukan atau malah memisahkan?
Baca juga: Polemik di Balik Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Tak sampai di situ, pengelolaan sekolah ini berada di bawah Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pendidikan akan direduksi menjadi proyek sosial belaka, bukan sebagai sistem penguatan kapasitas dan kecerdasan anak bangsa.
Jika pendidikan dianggap sebagai kebutuhan khusus, bukan hak dasar, maka negara telah gagal melihat rakyatnya sebagai subjek pembangunan yang setara. Anak-anak miskin bukan objek bantuan. Mereka warga negara penuh yang punya hak atas pendidikan berkualitas yang sama, bukan versi alternatif dari sistem utama.
Dari sisi anggaran, pendirian 200 sekolah rakyat memerlukan dana yang terbilang besar. Disebutkan bahwa setiap sekolah bisa menelan biaya hingga Rp100 miliar. Ini belum termasuk biaya operasional, gaji guru, fasilitas makan, transportasi, dan lain-lain.
Pertanyaan yang mengemuka kemudian ialah apakah pembangunan ini efisien secara fiskal? Sementara itu, ribuan sekolah negeri di berbagai pelosok negeri kekurangan guru, kekurangan sarana, dan bahkan bangunannya nyaris roboh. Kenapa justru negara memilih membangun institusi baru yang eksklusif?
Tidak berhenti di sana, kebijakan ini tampaknya juga dilandasi oleh pendekatan yang terlalu simplistis dalam memandang akar persoalan kemiskinan dan putus sekolah.
Berdasarkan data dari Survei Ekonomi Nasional (Susenas), alasan utama anak-anak putus sekolah bukan hanya soal biaya, tapi juga soal akses fisik, minimnya sarana pendukung, dan rendahnya relevansi pendidikan formal terhadap kebutuhan hidup sehari-hari.
Maka dari itu, membangun sekolah baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan tersebut. Justru yang dibutuhkan adalah transformasi menyeluruh atas sistem yang ada, mulai dari memperbaiki kurikulum, memperkuat kualitas guru, memperluas beasiswa, dan membuat sekolah negeri menjadi tempat yang inklusif untuk semua kalangan.
Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah indikasi bahwa Sekolah Rakyat bisa jadi bukan benar-benar upaya murni reformasi pendidikan, melainkan bagian dari agenda populis jangka pendek. Dalam politik, proyek yang kasat mata dan mudah difoto seringkali lebih disukai daripada pembenahan sistem yang tak terlihat secara langsung.
Sekolah Rakyat sangat fotogenik dengan instrumen gedung baru, anak-anak berseragam, bendera merah putih berkibar di ruang kelas. Namun, apakah itu cukup untuk menjamin perubahan? Atau justru hanya simbolisme kosong yang mengalihkan perhatian dari reformasi mendalam yang lebih dibutuhkan?
Sudah saatnya kita menyadari bahwa kesetaraan dalam pendidikan tidak bisa dibangun dengan menciptakan sistem paralel yang terpisah.
Kesetaraan hanya lahir jika semua anak, apapun latar belakang ekonominya, duduk di ruang kelas yang sama, belajar dari guru terbaik, dan memiliki harapan masa depan yang sama cerah. Sekolah Rakyat, dalam kerangka seperti sekarang, justru bergerak ke arah yang berlawanan dari cita-cita tersebut.
Penulis: Ahmad Bagus Kazhimi