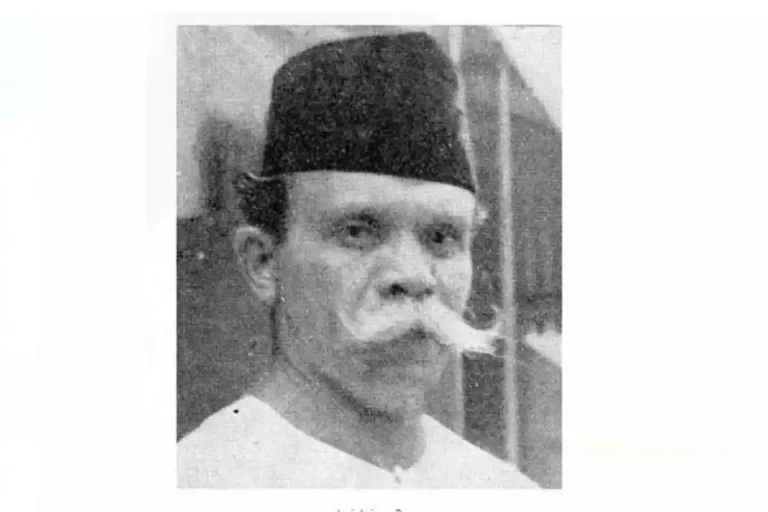Wacana pengangkatan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali mencuat dalam beberapa tahun terakhir, dan baru-baru ini wacana tersebut kembali menguat. Dukungan datang dari berbagai kalangan, termasuk keluarga, mantan militer, dan sebagian politisi. Namun, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional justru menjadi langkah problematik yang berpotensi memecah belah bangsa dan mengaburkan catatan sejarah.
Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan rezim Orde Baru yang dikenal otoriter. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat setidaknya 13.600 korban penghilangan paksa selama masa pemerintahannya.
Tragedi 1965-1966 menewaskan ratusan ribu hingga mungkin jutaan orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia. Peristiwa Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, dan penembakan misterius (petrus) 1983-1985 merupakan beberapa contoh pelanggaran HAM berat yang belum tuntas hingga kini.
Transparency International dalam laporannya menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia abad ke-20, dengan dugaan korupsi senilai US$15-35 miliar. Praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) menjadi sistemik selama pemerintahannya.
Lembaga Survei Indonesia mencatat bahwa 80% aset ekonomi nasional dikuasai oleh hanya 1% penduduk, kebanyakan kerabat dan kroni Soeharto. Data World Bank menunjukkan sekitar 30-40% dana pembangunan tahunan hilang akibat korupsi.
Krisis moneter 1998 yang menjadi pemicu jatuhnya Orde Baru memperlihatkan kerapuhan fondasi ekonomi. Kebijakan moneter yang tidak transparan dan hutang luar negeri yang membengkak hingga US$137,3 miliar menjadi beban negara.
Dari sisi lingkungan, program transmigrasi dan eksploitasi hutan menyebabkan kerusakan ekologis masif. World Resources Institute mencatat Indonesia kehilangan 20 juta hektar hutan selama periode 1985-1997.
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, seorang pahlawan nasional harus memenuhi kriteria: “perjuangannya berjasa terhadap bangsa dan negara, konsisten dalam perjuangan, memiliki semangat nasionalisme, dan berkelakuan baik.” Soeharto jelas tidak memenuhi kriteria “berkelakuan baik” mengingat catatan pelanggaran HAM dan korupsi yang meluas.
Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional juga jelas tidak tepat secara sosial dan politik. Hal ini tentu akan melukai korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, mengirim pesan keliru bahwa pelanggaran HAM dapat dimaafkan, menghambat proses rekonsiliasi nasional, dan mengaburkan pendidikan sejarah bagi generasi muda mendatang.
Alih-alih mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional, yang diperlukan adalah pembelajaran sejarah yang komprehensif. Negara perlu mengakui kesalahan masa lalu tanpa harus menguburnya dalam gelar pahlawan. Proses hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu harus terus diupayakan, sementara prestasi pembangunan dapat diakui secara proporsional.
Pengangkatan pahlawan nasional seharusnya menyatukan bangsa, bukan memecah belah. Soeharto mungkin layak dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi gelar pahlawan nasional hanya pantas diberikan kepada mereka yang jasanya tidak ternodai pelanggaran HAM dan korupsi sistematis. Biarlah sejarah mencatat Soeharto sebagaimana adanya: pemimpin kompleks dengan dua wajah, pembangunan dan kehancuran, yang warisannya masih kita perdebatkan hingga hari ini.