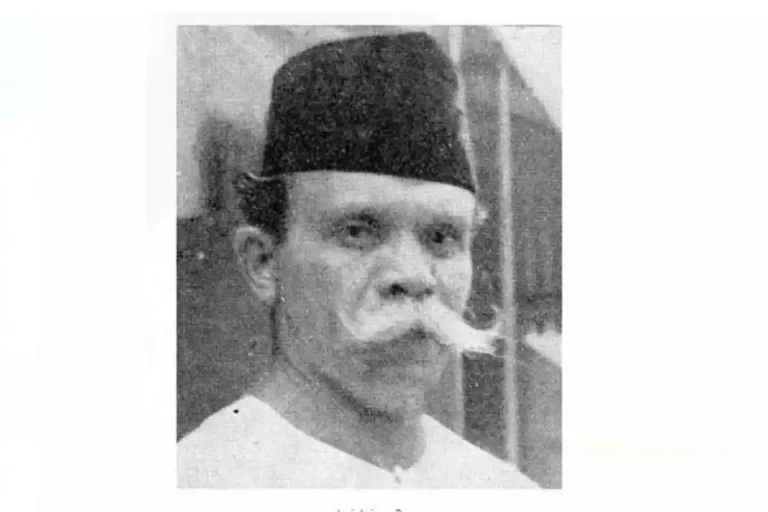Aksi demonstrasi selalu menjadi wajah nyata dari demokrasi. Di Indonesia sendiri demonstrasi kerap menjadi jalan terakhir ketika suara rakyat tidak lagi didengar melalui jalur formal. Akan tetapi, ketika demonstrasi besar-besaran terjadi pada akhir Agustus 2025 dan diikuti dengan penahanan ribuan massa oleh aparat, muncul pertanyaan penting: bagaimana komunikasi kekuasaan bekerja, dan sejauh mana relasi kuasa memengaruhi cara negara menghadapi suara rakyatnya?
Data konkret menunjukkan skala besar penahanan tersebut. Komnas HAM mencatat 951 orang ditahan dalam dua aksi unjuk rasa pada 25 dan 28 Agustus. Polri menyebut total 5.444 orang diamankan dari berbagai daerah buntut aksi kerusuhan, dengan sekitar 583 orang masih diproses hukum.
Angka yang lebih besar datang dari pernyataan pemerintah, yakni 6.719 orang ditahan sepanjang akhir Agustus, dengan 997 orang ditetapkan sebagai tersangka dan sekitar 5.858 dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.
Di Jakarta saja, Komnas HAM melaporkan 1.683 orang ditahan dalam gelombang demonstrasi 25–31 Agustus. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa penahanan massa bukan sekadar tindakan hukum, melainkan bagian dari praktik komunikasi politik.
Dalam kerangka ilmu komunikasi, demonstrasi adalah pesan politik rakyat. Harold D. Lasswell menjelaskan komunikasi sebagai proses “who says what, in which channel, to whom, with what effect”. Dalam kasus ini, rakyat (who) menyampaikan kritik (what) melalui aksi massa (channel) kepada pemerintah (to whom) dengan tujuan perubahan kebijakan (effect). Namun, ketika respons yang muncul justru berupa penahanan ribuan orang, maka pesan itu tidak hanya diabaikan, tetapi juga dihadapi dengan tindakan represif.
Pada titik inilah relasi kuasa berperan. Michel Foucault menegaskan bahwa kuasa tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif. Ia mendisiplinkan, mengatur, bahkan membentuk cara berpikir masyarakat secara luas.
Baca juga: Sekolah Rakyat Untuk Apa?
Penahanan massal adalah bentuk komunikasi kuasa negara yang menyatakan bahwa ada batas yang tidak boleh dilampaui dan bahwa negara menguasai ruang publik. Simbolisme ini menciptakan efek jera sekaligus rasa takut, sehingga masyarakat berpikir ulang sebelum turun ke jalan.
Namun, konsekuensinya adalah paradoks demokrasi. Negara yang seharusnya menjadi fasilitator komunikasi justru menjadi penghalang. Substansi tuntutan demonstran tereduksi karena publik dan media lebih banyak membicarakan bentrokan dan penangkapan ketimbang isu pokok.
Teori agenda-setting menjelaskan hal ini, di mana media cenderung menyoroti aspek dramatis dibanding substansi. Akibatnya, pesan rakyat tenggelam dalam framing negara dan media.
Lebih jauh lagi, dari perspektif ruang publik Habermas, demokrasi yang sehat membutuhkan arena di mana warga dan pemerintah bisa berdialog secara rasional. Demonstrasi sering muncul justru karena ruang formal untuk berdialog dianggap tidak efektif. Jika saluran alternatif ini pun ditutup dengan penahanan, maka ruang publik menyempit dan komunikasi berubah menjadi monolog kekuasaan.
Dalam jangka panjang, strategi represif ini juga bisa memunculkan efek spiral keheningan sebagaimana dijelaskan Elisabeth Noelle-Neumann. Masyarakat yang melihat risiko besar dari menyuarakan pendapat akan memilih diam. Namun, diam bukan berarti setuju; ia bisa menjadi akumulasi frustrasi yang sewaktu-waktu meledak lebih besar.
Dengan demikian, penahanan ribuan massa demonstrasi harus dipahami bukan sekadar sebagai tindakan hukum, melainkan praktik komunikasi kekuasaan yang sarat makna. Negara memang memiliki legitimasi untuk menjaga ketertiban, tetapi cara kuasa dijalankan menentukan kualitas demokrasi.
Jika penahanan terus dijadikan strategi utama, maka demokrasi berubah menjadi ruang semu di mana suara rakyat dibungkam melalui rasa takut. Sebaliknya, jika negara berani bergeser ke pendekatan dialogis, transparan, dan partisipatif, maka demonstrasi bisa dibaca bukan sebagai ancaman, melainkan indikator masalah yang butuh solusi struktural.
Akhirnya, demokrasi sejati tidak diukur dari seberapa sering rakyat diam, melainkan dari seberapa terbuka negara mendengar. Penahanan ribuan orang dalam demonstrasi terbaru di Indonesia seharusnya menjadi peringatan: suara rakyat tidak boleh hanya menjadi statistik, melainkan pesan politik yang wajib ditanggapi dengan serius.
Penulis: Ahmad Bagus Kazhimi